Sebuah Refleksi Populer atas Pemikiran Cardoso, Faletto, dan Peter Evans
Sebenarnya, dalam kehidupan bernegara, tidak semua keputusan lahir dengan sendirinya atau datang dari ruang hampa. Banyak di antaranya merupakan hasil dari tarikan kepentingan yang bersifat kompleks, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apalagi di negara-negara berkembang, keputusan strategis yang menyangkut ekonomi, politik, dan kebijakan publik sering kali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuatan eksternal dan kondisi internal yang tidak stabil. Inilah yang menjadi inti kajian para ilmuwan seperti Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, dan Peter Evans. Mereka mengajukan pandangan bahwa proses pengambilan keputusan di dunia berkembang sering kali merupakan hasil tawar-menawar antara kekuatan eksternal (misalnya dari lembaga keuangan internasional, negara maju dan perusahaan multinasional) serta dinamika internal seperti kekuatan kelompok elit, militer, dan birokrasi nasional.
Ketergantungan dan Struktur Dunia yang Tak Seimbang
Mencermati Cardoso dan Faletto, dalam karya klasik mereka Dependency and Development in Latin America, menjelaskan bahwa negara-negara berkembang berada dalam posisi struktural yang tidak setara dalam sistem dunia. Mereka tidak sekadar tertinggal secara ekonomi, tetapi juga bergantung secara struktural pada negara-negara maju, baik dalam hal modal, teknologi, maupun arah kebijakan^[1^]. Ketergantungan ini melahirkan apa yang mereka sebut sebagai “pembangunan yang tergantung” (dependent development), yaitu model pembangunan yang diarahkan oleh logika luar, tetapi dijalankan oleh elit lokal yang cenderung atau terlihat sebagai bersekutu dengan kepentingan asing.
Dalam konteks inilah maka keputusan negara berkembang—baik di bidang ekonomi seperti kebijakan utang luar negeri, privatisasi aset negara, maupun dalam bidang pertahanan seperti pembelian alutsista dan kerja sama keamanan—bisa jadi lebih mencerminkan kebutuhan pihak luar dibandingkan aspirasi rakyatnya sendiri. Ketika suatu negara memutuskan untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau membuka ruang investasinya secara luas, bisa jadi itu adalah hasil dari tekanan lembaga-lembaga seperti IMF atau World Bank, bukan semata-mata karena analisis kebutuhan domestik^[2^].
Peter Evans dan “State Embedded Autonomy”
Pada sisi lainnya, Peter Evans dalam karyanya Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, mencoba melihat dari sudut yang lebih optimis. Ia menyarankan bahwa meskipun ada tekanan dari luar, negara masih bisa menjadi aktor yang relatif otonom jika berhasil membangun birokrasi yang profesional dan “embedded”—tertanam dalam jaringan sosial dan ekonomi nasional^[3^]. Dengan kata lain, negara bisa tetap mengambil keputusan strategis yang berorientasi nasional jika memiliki aparatur negara yang kuat, transparan, dan mampu berinteraksi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil secara produktif.
Khusus mengenai hal ini, Evans mencontohkan keberhasilan beberapa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan dalam menghadapi tekanan luar tetapi tetap mampu mengarahkan kebijakan industri yang pro-nasional. Kuncinya, menurut Evans, adalah “autonomy with embeddedness”—negara tidak bisa terlalu tertutup (sehingga tidak tahu realitas pasar), tetapi juga tidak boleh terlalu terbuka (hingga dikuasai dengan mudah oleh pasar global).
Tekanan Global, Dinamika Nasional
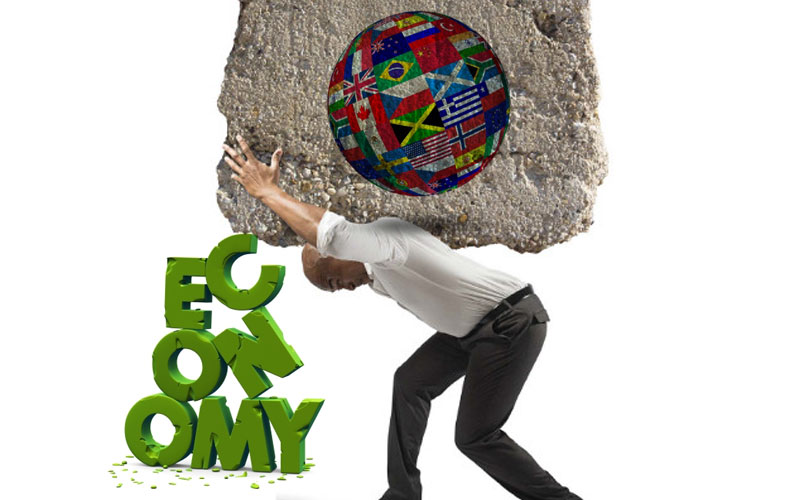
Dari dua pendekatan di atas memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, pengambilan keputusan di negara berkembang adalah sebuah proses negosiasi: antara tekanan eksternal dan struktur internal. Misalnya, ketika Indonesia pada 1998 mengalami krisis ekonomi dan akhirnya menerima bantuan IMF, keputusan-keputusan besar seperti pencabutan subsidi BBM, deregulasi pasar finansial, hingga reformasi perbankan bukanlah murni lahir dari pertimbangan internal, tetapi merupakan syarat yang ditetapkan oleh IMF dalam Letter of Intent^[4^]. Contoh yang jelas dan terang benderang dalam hal ini adalah dihentikannya proyek besar manufaktur pesawat N250 IPTN ketika itu.
Jadi dalam situasi seperti itu, aktor-aktor domestik tidak sepenuhnya berdaulat dalam menentukan arah kebijakan. Bahkan, mereka bisa jadi hanya berperan sebagai “perantara” yang menjembatani kepentingan asing dengan situasi nasional. Inilah yang dalam kajian pembangunan disebut sebagai “koalisi dominan”—gabungan antara elit politik dalam negeri dan kekuatan asing yang bersama-sama mengarahkan kebijakan negara.
Akan tetapi, tekanan luar negeri tidak selalu berbentuk paksaan langsung. Dalam banyak kasus, ia hadir dalam bentuk insentif—pinjaman murah, investasi asing, kerja sama militer, atau dukungan diplomatik. Negara yang ingin tetap “berdaulat” dalam mengambil keputusan sering kali harus memilih antara mempertahankan kebijakan nasional yang tidak populer secara internasional, atau menyesuaikan diri demi mendapatkan akses pada berbagai bentuk keuntungan tersebut. Gambaran ini juga dapat terlihat jelas pada perjanjian antara pemerintah RI dan Singapura tahun 2022 yang mencakup antara lain keputusan pendelegasian wewenang pengelolaan wilayah udara teritori Indonesia di kawasan paling rawan kepada Singapura.
Peran Elit dan Politik Dalam Negeri
Pada beberapa kasus, tekanan dari luar tidak serta-merta dapat menembus batas negara dan langsung mengubah arah kebijakan. Ia memerlukan saluran, aktor, dan kondisi politik domestik yang mendukung. Di sinilah pentingnya memahami peran elit nasional—baik itu pejabat pemerintah, teknokrat, militer, pengusaha besar, maupun politisi—yang sering kali menjadi perantara antara kepentingan asing dan kebijakan nasional.
Dalam hal ini, Cardoso dan Faletto menyebut kelompok ini sebagai “agen internal dari ketergantungan eksternal”^[5^]. Mereka bukan orang luar, tetapi warga negara sendiri yang justru memfasilitasi masuknya agenda eksternal. Dalam konteks ini, elit tidak selalu jahat atau korup. Sebagian besar dari mereka meyakini bahwa bekerja sama dengan kekuatan luar—seperti investor asing, lembaga donor internasional, atau negara maju—adalah cara tercepat untuk memajukan ekonomi atau menjaga stabilitas politik. Masalahnya adalah: kerja sama itu seringkali tidak dilakukan secara transparan, tanpa partisipasi publik, dan lebih mencerminkan kompromi elit ketimbang aspirasi rakyat banyak.
Sementara itu Peter Evans dalam penelitiannya di berbagai negara menekankan bahwa otonomi negara hanya bisa dijaga jika elit teknokrat dan birokrasi memiliki integritas dan tidak terlalu dekat dengan kepentingan bisnis atau asing^[6^]. Jika mereka terlalu “embedded” dalam jaringan oligarki domestik maupun asing, maka mereka akan kehilangan kemampuan sama sekali untuk bertindak menjadi penjaga kepentingan nasional.
Realitanya, dalam kasus Indonesia, peran elit ini terlihat sangat nyata dalam berbagai keputusan besar seperti privatisasi BUMN, proyek infrastruktur strategis berbasis utang luar negeri, dan bahkan dalam perjanjian kerja sama pertahanan. Sering kali, kebijakan-kebijakan itu diambil dalam ruang tertutup, tanpa kajian dampak yang transparan, dan dengan narasi yang lebih menekankan pada “kepentingan nasional” padahal sejatinya justru menguntungkan segelintir kelompok.
Yang harus diwaspadai, elit-elit ini memegang kendali atas lembaga-lembaga strategis seperti kementerian, parlemen, militer, bahkan media massa. Mereka membentuk koalisi kekuasaan yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas kepentingan antara luar dan dalam negeri. Dalam sistem demokrasi elektoral seperti di Indonesia, elit juga memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan siapa yang maju sebagai calon pemimpin melalui dukungan dana, jaringan, dan kendaraan partai. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang diambil kerap kali mencerminkan dan berorientasi penuh pada konsensus elit, bukan hasil deliberasi publik yang sehat.
Dengan demikian dalam kerangka ini, keputusan negara bukanlah hasil dari pertimbangan teknis rasional semata, tetapi juga merupakan cerminan dari relasi kuasa antara aktor-aktor domestik dan tekanan global. Negara menjadi arena kompromi dan pertarungan kepentingan, di mana yang paling kuat dan terorganisasi akan berhasil mempengaruhi hasil akhirnya.
Karena itulah, peran masyarakat sipil, media independen, dan lembaga-lembaga akademik menjadi sangat penting untuk mengawasi, mengkritisi, dan memberikan alternatif. Tanpa tekanan dari bawah, elite akan cenderung nyaman dalam persekutuan dengan kekuatan luar, dengan alasan pragmatisme atau stabilitas, padahal yang mereka abaikan adalah justru sebuah proses demokratis dan kepentingan rakyat dalam jangka panjang.
Kesimpulan: Mencari Ruang Keputusan yang Merdeka
Meneliti pemikiran Cardoso, Faletto, dan Evans, kita dapat melihat bahwa proses pengambilan keputusan di negara berkembang tidak bisa dilepaskan dari tarik menarik antara tekanan luar negeri dan dinamika dalam negeri. Negara bukan sekadar aktor netral, tetapi adalah medan pertarungan antara berbagai kepentingan. Dalam dunia yang makin terintegrasi, kedaulatan dalam pengambilan keputusan menjadi tantangan tersendiri—dan hanya bisa dicapai jika negara mampu memperkuat institusinya, memperkuat kapasitas teknokratiknya, dan menjaga otonomi politiknya di tengah gelombang besar tekanan global. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya pemimpin yang nasionalis, tetapi juga sistem yang kuat, birokrasi yang kompeten, dan masyarakat sipil yang kritis. Hanya dengan cara itu, keputusan-keputusan negara bisa benar-benar mencerminkan kepentingan rakyatnya, bukan sekadar hasil tekanan dari luar.
Catatan Kaki
- Cardoso, Fernando H., dan Enzo Faletto. Dependency and Development in Latin America. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton, 2002.
- Evans, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press, 1995.
- IMF. “Indonesia Letter of Intent,” 1998.
- Cardoso & Faletto, Dependency and Development, hlm. 161.
- Evans, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press, 1995, hlm. 12–15.
Daftar Referensi
- Cardoso, Fernando Henrique dan Enzo Faletto. Dependency and Development in Latin America. University of California Press, 1979.
- Evans, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press, 1995.
- Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company, 2002.
- Gereffi, Gary. “Global Production Systems and Third World Development.” In Global Change, Regional Response, edited by Barbara Stallings. Cambridge University Press, 1995.
- IMF. “Indonesia Letter of Intent 1998.” International Monetary Fund Archive.
- Robinson, William I. A Theory of Global Capitalism. Johns Hopkins University Press, 2004.
Jakarta 8 Mei 2025
Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia


